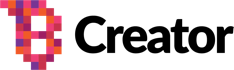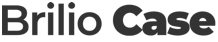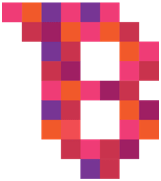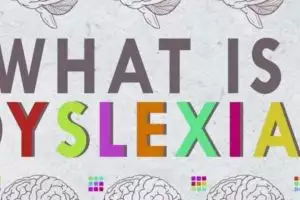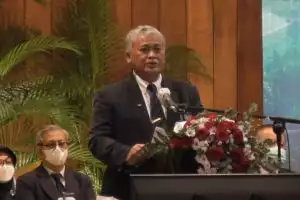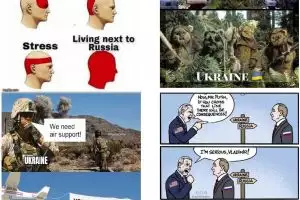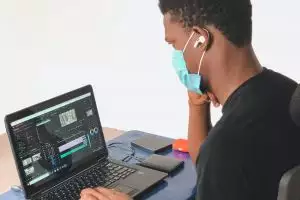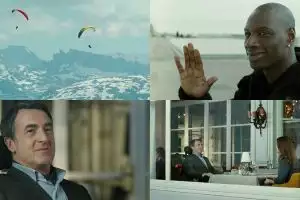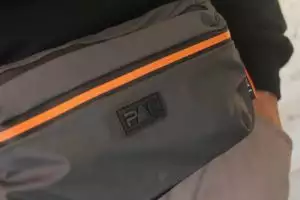Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengumumkan bahwa Gerhana Bulan Total (GBT) akan terjadi pada tanggal 28 Juli 2018 dan bisa dilihat di Indonesia. Gerhana bulan total yang terjadi ini diperkirakan terlama di abad 21, yakni 6 jam 17,3 menit.
Dalam rilis yang dikeluarkan BMKG, gerhana dimulai pukul 00.13 WIB dan ketika seluruh piringan Bulan memasuki umbra Bumi pada pukul 02:29,9 WIB, bagian Bulan menjadi memerah dan mencapai puncak kemerahannya pada saat puncak gerhana terjadi, yaitu pukul 03:21,7 WIB.
Memerahnya piringan Bulan ini terjadi karena adanya cahaya Matahari yang dihamburkan oleh atmosfer Bumi, untuk kemudian bagian cahaya kemerahannya yang diteruskan hingga sampai ke Bulan. Karena itulah, fase totalitas dalam Gerhana Bulan Total akan berwarna kemerahan.
Durasi totalitas, yaitu dari fase Gerhana Total mulai (U2) hingga Gerhana Total berakhir berlangsung selama 1 jam 43,6 menit.
Menurut rilis BMKG tersebut, lamanya durasi totalitas Gerhana Bulan Total 28 Juli 2018 tersebut disebabkan oleh tiga hal. Penyebab pertama adalah saat puncak gerhana terjadi, posisi pusat piringan Bulan dekat sekali dengan pusat Umbra Bumi.
Penyebab kedua adalah Gerhana Bulan Total 28 Juli 2018 terjadi pada saat Bulan di sekitar titik terjauhnya dari Bumi, yang dikenal sebagai titik apoge. Berdasarkan perhitungan, Bulan mencapai titik apoge pada 27 Juli 2018 pukul 12:44 WIB sejauh 406.223 km. Empat belas jam kemudian, tepatnya ketika puncak gerhana terjadi, jarak Bumi-Bulan menjadi lebih dekat 270 km daripada saat di apoge tersebut.
Secara umum semakin jauh jarak Bumi-Bulan akan semakin kecil tampakkan ukuran Bulan, sehingga berpotensi untuk menyebabkan Bulan akan lebih lama berada di umbra Bumi jika dibandingkan dengan Bulan saat berada di daerah titik perigenya. Dengan demikian, Gerhana Bulan Total pun berpotensi lebih lama.
Penyebab ketiga adalah pada bulan Juli Bumi sedang berada di sekitar titik terjauhnya dari Matahari, (aphelion), yaitu yang terjadi pada 6 Juli 2018 pukul 23:47 WIB dengan jarak 152 juta km. Pada saat puncak gerhana terjadi, jarak Bumi-Matahari adalah lebih dekat 184 ribu km dari saat di aphelion tersebut.
Secara umum, semakin jauh posisi Bumi dari Matahari, kerucut umbra yang terjadi menjadi semakin panjang dan lebih besar jika dibandingkan saat Bumi berada di sekitar titik terdekatnya dari Matahari. Karena itu, durasi totalitas Gerhana Bulan Total yang terjadi pun berpotensi menjadi lebih lama.
Mitos Masyarakat Jawa dan Relief Kalah Rahu di Candi Belahan
Peristiwa gerhana bulan sudah dikenal oleh masyarakat Jawa Kuno. Bahkan ada sebuah relief yang menggambarkan peristiawa ini, tepatnya di Candi Belahan Sumber tetek, lereng Gunung Penanggungan di sisi timur.
Dalam relief tersebut tergambar bagaimana orang dulu menggambarkan peristiwa ini dengan gambaran sosok raksasa yang kedua tangannya memegang benda bulat dan memasukkannya ke mulut. Raksasa itu juga dikawal oleh tiga sosok yang berada di sebelahnya.
Arkeolog Universitas Negeri Malang, M Dwi Cahyono menjelaskan bahwa ada beberapa pendapat mengenai penjelasan relief ini. Yakni, terkait peristiwa mangkatnya Raja Mataram terakhir, Raja Airlangga dan peristiwa terbelahnya kerajaan Mataram menjadi dua, yakni Kerajaan Kadiri dan Panjalu.
Di sekitar relief juga ada penggambaran tiga sosok dengan posisi terbang yang oleh ahli, kata Dwi Cahyono dibaca seabgai chandrasangkalaatauchandraresi rahu,chandraartinya 1resiadalah 9 danrahuartinya 7 atau 971 Saka. Dalam penanggalan Masehi sekitar 1049.
Pendapat lain membacanya sebagai rahu anahut chandra, chandraartinya 1,anahutadalah 3 danrahuartinya 9 atau 931 Saka. Dalam penanggalan Masehi sekitar 1009. Sedangkan pendapat lain tegas menyebut relief Candi Belahan menunjukkan gerhana terjadi sekitar pukul 04.00 WIB pada 7 Oktober 1009 Masehi.
Menurut Dwi Cahyono, masyarakat Jawa pada waktu itu memiliki kepercayaan peristiwa gerhana bulan karena bulan lenyap ditelan raksasa. Gerhana matahari atau bulan dalam mitologi Jawa ditelan raksasa atau disebutKala Rahu.
Sehingga, kata Dwi Cahyono, muncul beberapa tradisi memukul bebunyian atau tetabuhan sebagai gambaran masyarakat yang berusaha mempertahankan matahari dan bulan agar tak ditelanKala Rahu.
Masyarakat mengejarKala Rahu dengan memainkan alat musik bertalu-talu, menggunakan tampah, wajan, solet dan lesung agar Kala Rahu melepas atau memuntahkan matahari atau bulan.
"Tradisi ini berlangsung secara turun temurun dan biasa disebut Bendrong sebagai reaksi atas lenyapnya matahari atau bulan," ujarnya.