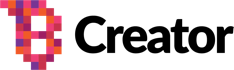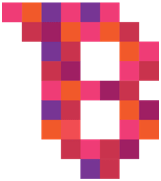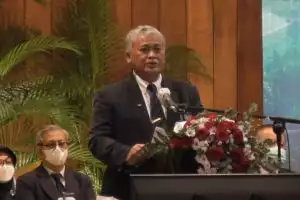Ketika saya tinggal di pedesaan Jepang 10 tahun lalu, saya jarang melewati pemukiman warga pendatang.
Bahkan di Tokyo, sebagai orang Amerika Serikat berkulit putih nan jangkung, saya sering dilihat dengan aneh oleh penduduk lokal.
Namun ketika saya berkunjung ke negara itu November lalu, saya kaget betapa Jepang telah berubah. Setiap hotel, pusat perbelanjaan, dan kafe sepertinya mempekerjakan setidaknya satu imigran.
Beberapa anak muda yang berjaga di resepsionis dan pusat gim video tidak menggunakan label nama bertuliskan huruf kanji.
Berkebun, hobi yang mungkin membantu Anda hidup sampai usia 100
Kisah pasangan yang untuk pertama kalinya tak rayakan Natal bersama dalam 73 tahun terakhir
Ikumen: Cara para 'ayah ganteng' di Jepang mengubah peran orang tua
Di sebuah bar-restoran di Kanazawa, kota di utara Tokyo yang hampir seluas ibukota Jepang itu, saya melihat orang Kaukasia menjadi asisten juru masak sushi.
Di restoran lainnya, kami bertemu pelayan dari negara Asia lainnya sebelum akhirnya berbincang dalam bahasa Inggris.
Singkatnya, Jepang telah membuka diri terhadap dunia luar dan proses itu berada pada puncak akselerasinya.
Faktor utamanya adalah perbuahan demografi: populasi Jepang semakin menua dan kelompok muda-mudinya menyusut.
Ditambah faktor pariwisata yang melesat jauh dibandingkan sebelumnya, serta persiapan besar-besaran jelang Olimpiade 2020, hasilnya: Jepang sangat membutuhkan tenaga kerja.
Jepang telah mengetahui kegentingan demograafi itu beberapa dekade sebelum ini. Namun karena pemerintah enggan mengambil langkah strategis, persoalan ini membesar.
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, ingin mendatangkan lebih banyak tenaga kerja asing berupah rendah.
Meski begitu, rencananya menerima ribuan warga asing untuk mengisi pekerjaan kerah biru hingga 2025 sangat kontroversial di negara yang berjarak dengan imigran.
Pada 9 Desember lalu, parlemen Jepang menerima usulan Abe itu melalui perdebatan panjang. Jepang mempekerjakan pekerja migran dalam jumlah yang tak pernah mereka jalankan sebelumnya: 300 ribu pekerja asing dalam lima tahun ke depan, terhitung sejak April 2019.
Undang-undang baru itu muncul sebagai perubahan bersejarah di Jepang. Dan yang terjadi akan mengubah negara itu selama beberapa generasi ke depan.
Manula bertambah, orang asing makin banyak
Bhupal Shrestha adalah dosen yang tinggal di kawasan Suginami, Tokyo, sebuah pemukiman yang dikenal dengan gang sempit serta toko pakaian bekas dan barang antik.
Shrestha sudah tinggal di Jepang selama 15 tahun, tapi perjalanannya mendapatkan izin tinggal permanen tidaklah mulus.
Shrestha mengklaim mengalami diskriminasi, bahkan terkait perihal dasar seperti saat mencari tempat tinggal atau tempat usaha, membuka rekening bank, dan mengajukan kartu kredit. Dia menyebut imigran sulit mengkritik kebijakan pemerintah lokal yang menyulitkan mereka.
"Masyarakat Jepang tengah membuka diri mereka terhadap imigran, tapi di beberapa daerah, penduduk tetap konservatif," ungkap Shrestha.
"Menurut saya ini terjadi karena mereka tak berkesempatan bergaul dengan imigran," imbuhnya.
Berasal dari Nepal, Shrestha adalah satu dari 1,28 juta pekerja asing di Jepang. Angka itu merupakan rekor, naik dari 480 ribu pada tahun 2008.
Namun, angka itu hanya sebesar 1% dibandingkan total populasi Jepang. Seagai komparasi, persentase di Inggris mencapai 5% dan 17% di AS.
Hampir 30% pekerja asing di Jepang merupakan warga Cina, disusul Vietnam, Filipina, dan Brasil.
Jumlah yang minim itu disebabkan isu imigrasi yang tak populer di Jepang. Sebagai negara kepulauan, Jepang pernah sangat terisolasi dari dunia luar.
Pada pertengahan abad ke-19, orang yang masuk atau meninggalkan Jepang bahkan dapat dijatuhi hukuman mati. Jepang saat ini sangat homogen dengan identitas kultural yang kuat.
Merujuk sejarah, rasa waswas Jepang terhadap imigran disebabkan pada kekhawatiran kehilangan lahan pekerjaan, gangguan budaya, hingga kekhawatiran meningkatnya kejahatan di negara yang terkenal rendah angka kriminalitas itu.
Namun persoalan sebenarnya adalah jumlah penduduk asli Jepang yang terus menurun.
Populasi Jepang berkurang hampir satu juta orang dari sejak 2010 hingga 2015. Tahun 2017, jumlah penduduk negara itu berkurang 227 ribu orang.
Pada periode yang sama, jumlah penduduk berusia di atas 65 tahun mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 27% dan diperkirakan meningkat sampai 40% pada 2050.
Mei lalu, rasio ketersediaan pekerjaan pun mencapai titik tertinggi selama 44 tahun terakhir: 160 lowongan untuk setiap 100 pekerja.
Artinya, saat ini terdapat banyak sekali lowongan pekerjaan yang tak cocok untuk penduduk usia lanjut, tapi di satu sisi juga tidak diinginkan generasi muda.
"Sangat serius," kata Shihoko Goto, peneliti senior di lembaga riset berbasis di AS, Woodrow Wilson Center, menanggapi persoalan itu.
Namun Goto mengatakan, selama ini keran imigrasi tidak dianggap sebagai solusi tepat untuk sejumlah permasalahan yang dihadapi Jepang.
Ketika sejumlah pelaku bisnis dan politikus mendukung rencana Shinzo Abe soal imigran, beberapa pihak lain mempertanyakan efektivitas kebijakan itu.
Putus asa mencari pekerja
"Tidak banyak warga Jepang yang pernah bekerja dan tinggal bersama warga asing," kata Masahito Nakai, advokat di Tokyo yang giat beracara pada kasus imigrasi.
Namun Nakai menyebut penduduk Jepang mulai menyadari bahwa hal baru benar-benar harus dilakukan. "Mereka sadar, Jepang tidak akan bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri," tuturnya.
Sektor konstruksi, pertanian, galangan kapal di seluruh Jepang sangat membutuhkan tenaga kerja. Industri perhotelan dan ritel belakangan membutuhkan penutur bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya agar pariwisata tetap dapat berjalan.
Dibutuhkan pula tenaga perawat dan asisten rumah tangga seiring pertumbuhan pesat kelompok warga usia lanjut.
Data November lalu menunjukkan, dalam lima tahun ke depan lebih dari 345 ribu pekerja asing akan masuk ke Jepang untuk mengisi posisi yang lowong itu. Syaratnya, usulan kebijakan Abe harus lolos di parlemen.
Saat ini pemerintah Jepang mengizinkan program pelatihan atau magang teknis terkait pekerja asing. Kebijakan itu memungkinkan buruh atau pelajar bekerja dengan upah rendah selama tiga hingga lima tahun sebelum kembali ke negara asal.
Akan tetapi, program itu dikritik karena mengeksploitasi pekerja, dari upah yang amat kecil sampai lingkungan pekerjaan yang buruk.
Tahun 2017, seorang pemuda berusia 24 tahun asal Vietnam diketahui bekerja menangani limbah radioaktif nuklir pada program pembersihan Fukushima.
Media massa lokal mengkritik kebijakan itu bertahun-tahun. Sebagian menyebut Jepang menerapkan perbudakan terselubung.
Kini Abe berencana mengizinkan pekerja dengan keterampilan rendah tinggal di Jepang selama lima tahun. Ia juga mengusulkan prosedur perpanjangan visa untuk pekerja terampil, yang diizinkan membawa keluarga mereka.
Abe menargetkan, skema baru pengurusan visa itu dapat diterapkan April 2019.
Abe berkeras menyebut para pekerja asing itu sebagai imigran. Para kritikus khawatir rencana Abe menyediakan peluang besar bagi para imigran untuk menerima izin tinggal tetap.
Ada pula kekhawatiran bahwa pekerja asing akan memenuhi perkotaan dan tidak tinggal di pedesaan, wilayah yang sangat membutuhkan tenaga mereka.
Pegiat hak asasi manusia cemas, masyarakat Jepang belum mengetahui batas untuk tidak mengeksploitasi pekerja asing.
Takatoshi Ito, guru besar kebijakan publik dan internasional di Universitas Columbia, yakin masyarakat Jepang telah menyadari arti globalisasi.
"Sejauh ini, mayoritas pekerja asing menopang pertumbuhan ekonomi. Mereka mengisi pekerjaan yang tidak disukai warga lokal," ujarnya.
Namun Nakai, menyebut jaminan visa hanyalah awalan. Proses asimilasi mereka dengan budaya Jepang merupakan tantangan besar.
Pengacara imigrasi itu menunjuk ketimpangan pengetahuan bahasa dan budaya sebagai hambatan terbesar yang akan dihadapi para pekerja asing.
"Jika para wajib pajak setuju, pemerintah setidaknya akan menyediakan kursus bahasa Jepang yang gratis atau berbiaya murah, di seluruh penjuru Jepang, sebagai langkah awal," kata Nakai.
Sejumlah pihak menganggap sebenarnya tidak ada persoalan besar dalam isu imigrasi ini.
"Sangat sedikit acara silang budaya yang digagas. Di antara tetangga apartemen saja komunikasi sangat minim," ujar Bhupal Shrestha.
"Ketika tak ada pemahaman bersama di antara tetangga, masyarakat yang multikultural tidak mungkin terwujud."
Bentrokan budaya
Chikako Usui, pakar sosiologi di Universitas Missouri di St Louis, AS, menyebut sejumlah faktor yang mungkin menyulitkan imigran, dari sejarah ketertutupan Jepang hingga penduduk yang homogen.
Usui menyoroti harapan terhadap aturan tersembunyi dan semangat komunal yang membuat masyarakat Jepang tak nyaman dan waswas pada orang asing.
Persoalannya, kata Usui, bagaimana warga asing dapat memahami seluruh kebiasaan orang Jepang, dari tata cara daur ulang, tidak berisik di kendaraan umum hingga mengantisipasi pikiran orang lain.
Usui menyebut konsep tradisional Jepang 'kuuki wo yomu' atau 'membaca udara' yang membentuk masyarakat negara itu serta secara telepatis mengerti secara rinci aturan sosial.
"Warga Jepang tak yakin itu bisa dilakukan warga asing. Faktanya, saya sendiri juga tidak selalu bisa menerapkannya di Jepang," tuturnya.
Goto, dari Woodrow Wilson Center, menyebut terdapat kode etik tersendiri yang berlaku bagi warga Jepang.
"Ini bukan tentang kewarganegaraan, ini tentang ras, bahasa, dan bahasa tubuh. Seluruh hal halus ini tidak akan diraih warga asing."
"Namun ada perspektif terbuka yang terus meningkat," ujar Goto.
"Saya rasa orang Jepang punya lebih banyak peluang bersosialisasi dengan orang asing, dalam situasi yang tak mereka pikirkan, bahkan 10 tahun lalu," ucapnya.
Seiring populasi yang semakin tua dan hajatan Olimpiade yang semakin dekat, tekanan untuk mendatangkan pekerja dari luar negeri terus menguat.
Mereka yang pindah ke Jepang perlu tahu negara seperti apa yang mereka datangi, kata Shrestha.
Dia menikmati tinggal di Jepang, tapi menyebut tempat itu sebagai tempat di mana etos kerja diagungkan dan peraturan sangat dipatuhi.
"Sangat disarankan datang dengan pengetahuan tentang budaya Jepang dan aturan dalam kehidupan kesehariannya," kata Shrestha.
Sementara itu, pemerintah Jepang sepertinya akan menghabiskan 2019 untuk bergelut tentang solusi pekerja asing. Sebelum pro dan kontra itu selesai, persoalan tenaga kerja masih akan tetap ada.