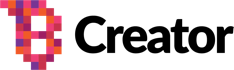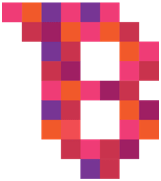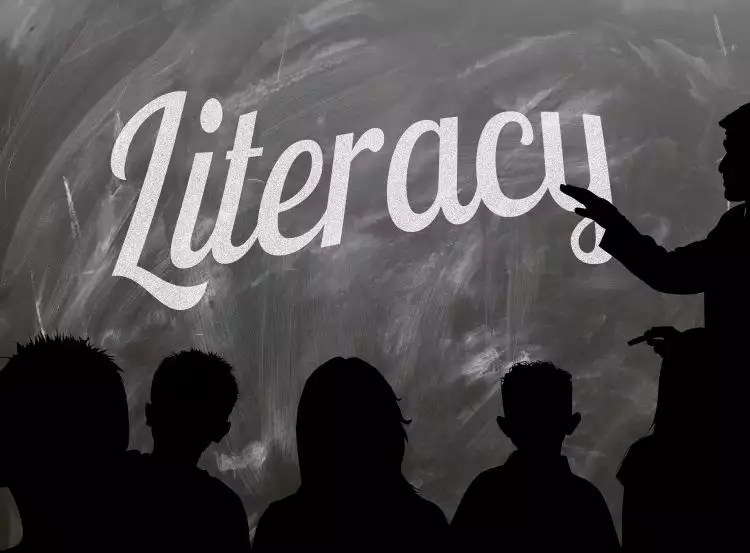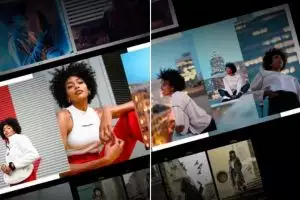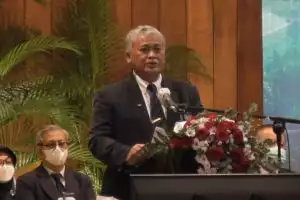Pada tahun 2012, hasil temuan Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan bahwa budaya literasi Indonesia berada di urutan ke-64 dari total 65 negara. Masih di tahun yang sama, The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) melaporkan indeks minat baca kita baru mencapai 0,001. Artinya, dari 1000 penduduk, hanya satu yang punya minat baca. Di tahun 2016 lalu, hasil penelitian The Worlds Most Literate Nation yang dilakukan oleh The Central Connecticut menunjukkan dari 61 negara, Indonesia berada di urutan ke-60 sebagai negara dengan minat baca rendah. Artinya setelah empat tahun berlalu belum terjadi perubahan yang mengarah pada peningkatan.
Barangkali ini juga yang melatarbelakangi alasan mengapa akhir-akhir ini literasi menjadi isu yang semakin penting dalam konteks pendidikan di Indonesia. Apalagi dalam revolusi industri 4.0 sekarang persaingan antar bangsa semakin terbuka dan kompetitif. Pemerintah dan para praktisi pendidikan menyadari betul bahwa dengan literasi yang berkualitas, masyarakat akan siap menghadapi tantangan global. Maka tak heran bila dalam kurikulum 2013 versi terbaru, sekolah-sekolah diwajibkan mengadakan kegiatan literasi sebelum pelajaran dimulai.
Berbagai tantangan yang terjadi.
Kebijakan mewajibkan gerakan literasi pada peserta didik perlu diapresiasi. Namun jika budaya membaca dilakukan hanya sebatas pada saat sebelum pelajaran dimulai di sekolah, tentu hasil yang akan diperoleh tidak akan berpengaruh banyak. Generasi muda perlu waktu yang lebih dari itu untuk bisa mulai mengakrabkan diri dengan rutinitas membaca.
Selain minat membaca kita yang masih sangat rendah, ada persoalan-persoalan lain yang menjadi penghambat budaya literasi dan harus mendapatkan perhatian yang serius dan disikapi secara cermat. Yang pertama adalah masalah ketersediaan buku. Distribusi buku di kota dan di pedesaan sangat timpang. Kedua, buku-buku berkualitas juga harganya cenderung mahal sehingga sulit dijangkau sebagian besar masyarakat kita. Ketiga, ketidaksesuaian jenis literatur yang tersedia dengan kebutuhan pembaca. Keempat, jumlah buku yang diproduksi di Indonesia tergolong sedikit. Menurut International Standard Book Number (ISBN) pada tahun 2016, negara kita hanya memproduksi 64 ribu buku per tahun. Dibandingkan dengan negara-negara maju semisal Tiongkok, kita masih kalah jauh. Mereka bisa memproduksi buku hingga mencapai angka 440 ribu tiap tahunnya.
Artinya, polemik literasi di Indonesia yang begitu rendah berdasarkan temuan-temuan beberapa lembaga tadi tidak boleh hanya dilimpahkan pada pemerintah semata. Pihak-pihak lain seperti masyarakat, para pakar pendidikan hingga penulis dan perusahaan-perusahaan penerbit buku, harus saling berkolaborasi untuk membangun budaya literasi yang sehat dan berkualitas.
Paradoksera digital.
Kecanggihan zaman di masa sekarang seharusnya bisa mengakomodir peningkatan literasi di Indonesia. Dengan gawai (gadget) yang begitu digandrungi segenap lapisan masyarakat kita, akses informasi serta konten bacaan berkualitas bisa diakses dengan mudah setiap harinya karena terkoneksi dengan internet. Padahal jumlah pengguna internet di negara kita termasuk dalam kategori yang tinggi. Survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa penetrasi pemakaian internet mencapai 143,26 juta pengguna atau sekitar 54, 86 persen dari total populasi manusia Indonesia. Dan 49,52 persen pengguna internet adalah kaum muda yang sering disebut generasi milenial.
Perangkat ponsel pintar (smartphone) seyogyanya menjadi alat bagi penggunanya, terutama generasi milenial untuk bisa melahap sumber bacaan yang bisa meningkatkan kecerdasan seperti jurnal penelitian dari berbagai disiplin ilmu, buku-buku elektronik (e-book) fiksi maupun non-fiksi dan masih banyak lagi.
Tapi memang harapan (expectation) sering kali tidak jalan dengan kenyataan (reality). Masyarakat kita memiliki kecanduan yang begitu akut pada ponsel pintar. Mereka bisa tahan berjam-jam di depan layar gawai. Sayangnya waktu yang begitu lama ini lebih cenderung dihabiskan untuk aktivitas-aktivitas yang berkontribusi minim pada peningkatan minat membaca. Mereka lebih suka membaca atau menulis status di media sosial, melakukan swafoto yang kemudian diunggah sehingga mengundang tanggapan dari pengguna media sosial lain. Akhirnya waktu terbuang hanya untuk saling balas komentar. Maka tak heran bila muncul stigma bahwa ponsel pintar menjadikan penggunanya bodoh.
Belajar darimasa lalu.
Kita seharusnya malu dan berkaca pada masa lalu. Zaman dulu ada begitu banyak penulis-penulis hebat dengan karya-karya berkualitas yang muncul karena daya pikir kritis dan analitis. Nama-nama besar seperti Pramoedya Ananta Toer, Chairil Anwar, Sitor Situmorang, Soe Hok Gie, hingga salah satu founding father kita, Mohammad Hatta adalah segelintir contoh orang-orang yang mampu menelurkan buah pemikiran hebat di era serba sulit.
Mereka mampu berkarya sudah pasti karena minat baca yang begitu tinggi. Padahal jika dibandingkan, pada masa mereka jangankan akses internet, buku-buku referensi ilmu pengetahuan berbahasa Indonesia saja jumlahnya sangat terbatas. Akhirnya mereka harus berjibaku membaca buku-buku berbahasa asing. Tapi situasi sulit ini justru berhasil menempa mereka menjadi manusia-manusia yang memiliki kecerdasan tinggi. Dan memang kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Mereka menjadi tokoh-tokoh yang begitu dikagumi di masa sekarang.
Bung Hatta pernah berujar, Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Tokoh-tokoh yang hidup di masa serba susah ini saja begitu menyadari bahwa literasi memiliki peran sentral dalam memperbaiki kehidupan. Sebab buku sebagai jendela informasi tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka kita yang hidup di zaman sekarang dengan segudang kemudahan tidak punya alasan untuk tidak mengikuti jejak sosok inspiratif-inspiratif seperti mereka. Maka mulailah menggiatkan membaca dari sekarang.
Gerakan literasi harus dipupuk secara berkelanjutan. Anak-anak muda harus mau sadar akan pentingnya membaca. Mereka harus bisa melawan rasa malas membaca. Membaca secara tuntas mesti dijadikan sebagai rutinitas yang wajib. Langkah awal bisa dilakukan dengan cara memilih buku-buku fiksi atau nonfiksi yang isinya berkaitan dengan minat (interest) masing-masing individu sehingga tidak akan cepat merasa bosan. Entah itu buku dalam wujud kertas atau elektronik yang bisa diperoleh dan dibaca lewat ponsel pintar atau laptop, yang jelas membaca harus dijadikan sebagai kebutuhan.
Selain itu, perlu juga dibuat target yang harus dicapai. Misalnya dalam jangka satu bulan harus selesai membaca satu atau dua buku. Kemudian secara bertahap asupan bacaan harus mulai ditingkatkan, baik dari segi kuantitas atau kualitas bacaan dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian antara usia dan konten bacaan.
Agar proses membaca bisa semakin mengasah pola berpikir kritis dan analitis, ada baiknya membaca sebagai kegiatan reseptif dilakukan secara beriringan dengan aktivitas reflektif dan menghasilkan output seperti membuat resensi atau critical book review. Dengan cara ini generasi muda kita tidak hanya akan menjadi pembaca aktif dan kritis (active and critical readers) tapi juga bisa secara perlahan beralih menjadi penulis yang konstruksi berpikirnya akan semakin luas.
*Penulis adalah Alumnus Pascasarjana Unimed berprofesi sebagai Guru SMP/SMA Sutomo 2 Medan dan Dosen PTS.
Source
- https://www.google.com/search?q=gambar+budaya+literasi&safe=strict&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XyphpIEywLR-CM%253A%252C_aL182egVb47TM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTtS-yvvnLM0QshTmpgKagad5D3fw&sa=X&ved=2ahUKEwj91d694rHhAhWA4HMBHfnUCB8Q9QEwBHoECAkQDA#imgrc=XyphpIEywLR-CM: