Awal Agustus, portal berita gosip Lambe Turah dihebohkan dengan postingan curahan hati seorang selebritas. Ia merasa sakit hati dengan perlakuan seorang wanita yang telah menuduh mamanya sebagai ibu yang kejam dalam mendidik anak. Gara-garanya, sang mama bertindak tegas pada kakak laki-lakinya yang seorang penyandang autis ketika sedang tantrum di sebuah mall. Sang anak tidak terima perlakuan wanita yang telah menegur dan menuduh mamanya sebagai ibu yang kejam terhadap anaknya. Tulisan ini hendak menelusuri mengapa sampai ada seorang wanita yang men-judge seorang ibu yang menurutnya berperilaku kejam dalam mendidik anaknya. Ada beberapa kemungkinan yang bisa dijadikan latar belakang alasan perilaku wanita tersebut.
1. Kurangnya pengetahuan terhadap apa itu autisme, ciri-ciri penyandangnya, serta bagaimana mesti bersikap pada mereka dalam kehidupan sehari hari.
Pada dasarnya, autisme merupakan gangguan perkembangan pada anak. Gejalanya sudah tampak sebelum anak mencapai usia tiga tahun. Gangguan perkembangan pada anak autis meliputi tiga aspek, yakni komunikasi dan bahasa, interaksi sosial, dan perilaku. Gangguan ini pada umumnya juga akan diikuti gangguan pada aspek motorik kasar dan motorik halus, persepsi visual, emosi yang selanjutnya akan menghambat perkembangan kognitif dalam konteks masa sekolah. Gejala gangguan tersebut dapat dilihat pada usia 2-3 tahun, di mana anak pada umumnya mulai belajar bicara. Anak autis tidak menampakan tanda-tanda perkembangan bahasa dan bicaranya. Namun dalam beberapa kasus, anak autis dapat mengeluarkan kata-kata, tapi terkesan aneh, masyarakat pada umumnya menyebutnya sebagai bahasaplanet.
Gangguan dalam perkembangan anak-anak autis yang meliputi tiga bidang di atas termanifestasikan dalam bentuk yang sangat beragam. Mereka cenderung suka menyendiri, tidak mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan teman sebayanya, cara bermainnya tidak imajinatif dan cenderung monoton. Lazim ditemui perilaku anak-anak autis terlihat berbeda dari anak-anak pada umumnya, misalnya melakukan gerakan unik yang diulang-ulang, mondar mandir tidak jelas tujuannya, berputar-putar, mengepak-ngepakan tangannya seperti sayap, cenderung aktif, terpukau pada benda-benda tertentu (benda yang berputar), suka memperhatikan gerakan jari tangannya sendiri secara terus menerus dan acuh tak acuh terhadap kejadian dan keadaan sekitarnya, tidak dapat berbicara, dan juga kesulitan dalam berkomunikasi secara non verbal.
Karena manifestasi autisme yang menyebabkan para penyandang autisme menunjukkan ciri-ciri perilaku berbeda dari kebanyakan orang, berkembang cara pandang yang cenderung merendahkan penyandang autisme. Lalu, bagaimana menyikapi bila kita bertemu dengan mereka? Perlakukan mereka seperti halnya orang atau anak pada umumnya. Jika kita dalam kondisi yang mesti berinteraksi, lakukan interaksi seperti biasa. Pada umumnya, penyandang autis yang mampu berkomunikasi, bisa melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Sementara bagi mereka yang masih atau tidak dapat berkomunikasi secara verbal, umumnya akan didampingi orang lain.
Bagaimana bila kita menjumpai mereka dalam kondisi ketika mereka sedang tantrum (ledakan emosi), maka sebaiknya kita tidak memandanginya lebih dari 5 menit. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga perasaan keluarga atau pendamping penyandang autis. Tentu sangatlah tidak menyenangkan bila kita dalam kondisi sedang berusaha menenangkan anak yang sedang tantrum, kemudian diperhatikan oleh orang-orang lain, terlebih bila ada yang berkomentar. Akan lebih baik, kita memberikan ruang bagi mereka untuk menenangkan diri dengan tidak menjadikan mereka tontonan, atau bahkan melontarkan komentar yang tidak perlu, seperti Kenapa sih teriak teriak atau Memang minta apa, sudah diturutin saja maunya, pokoknya diam.
2. Kurangnya sosialisasi terkait autisme yang benar terhadap masyarakat.
Akibatnya, fenomena perundungan dalam bentuk verbal sebagaimana yang dilakukan wanita tersebut dapat terjadi. Istilah autisme di Indonesia sampai tahun 1990-an masih merupakan suatu istilah yang belum dikenal secara luas oleh masyarakat, kecuali oleh orang tua yang memiliki anak penyandang autisme. Di masa ini, media kurang berperan dalam meliput maupun membahas masalah autisme secara mendalam apalagi tuntas. Sejak tahun 1998, di mana arus informasi meningkat pesat karena internet, sebenarnya tersedia beragam penjelasan yang memengaruhi cara pandang tentang autisme. Pada masa ini banyak bermunculan situs maupun blog pribadi yang membahas tentang autisme, baik sekadar untuk berbagi pengalaman tentang anak sendiri maupun menyediakan informasi lengkap tentang autisme. Media pun mulai tertarik meliput berita seputar autisme. Hasilnya sedikit demi sedikit masyarakat luas mulai menyadari kehadiran penyandang autis yang berbeda dengan anak-anak lain. Kata autis pun mulai marak bermunculan di media cetak maupun elektronik.
Sayangnya, seiring dengan mulai dikenalnya istilah autis secara luas di masyarakat, istilah tersebut juga kerap digunakan dengan konotasi negatif atau sebagai bahan lelucon oleh berbagai pihak. Sebuah survei yang pernah dilakukan sebuah media online terhadap pemahaman masyarakat tentang istilah autisme menunjukkan kecenderungan negatif tersebut. Hasil survey yang respondennya adalah masyarakat umum tersebut menemukan bahwa masyarakat Indonesia belum paham benar tentang autisme. Hal ini ditandai dengan pandangan mereka yang menyebutkan autisme sebagai suatu penyakit bahkan penyakit menular; autis tidak dapat diobati, autis sama dengan gangguan jiwa; autis sama dengan keterbelakangan mental atau autis sama dengan sindrom bawaan sejak lahir. Para responden juga menyebut karakteristik penyandang autis yang mereka ketahui antara lain: terlalu fokus pada sesuatu hingga seperti memiliki dunianya sendiri yang berbeda dengan orang pada umumnya, senang tertawa sendiri, tidak mau diganggu, memiliki kelebihan yang menonjol dari orang normal seperti mudah menghafal, lebih cerdas, mempunyai semangat yang tinggi, gerakan dan perilakunya cenderung aktif bahkan hiperaktif, serta memiliki kelakuan berbeda dengan orang pada umumnya
3. Kebiasaan untuk cepat mengambil kesimpulan dan menghakimi orang lain yang dianggapnya tidak berperilaku sesuai standar norma kepantasan di masyarakat.
Tanpa mengetahui latar belakang, suatu tindakan diambil. Kebiasaan ini sebagai akibat kurangnya budaya listening pada sebagian dari masyarakat kita. Kita lebih terbiasa berbicara dibanding listening. Mengapa listening, bukan hearing? Karena kedua hal tersebut berbeda, meski artinya sama, yakni mendengar. Hearing artinya mendengar, dikaitkan dengan fungsi fisiologis, Sementara listening merupakan istilah yang berarti ketrampilan mendengar, yang dipelajari sebagaimana halnya kita mempelajari membaca atau menulis. Listening menurut Wood (2004) merupakan proses yang aktif dan kompleks karena melibatkan telinga, hati, dan pikiran untuk menyeleksi dan mengorganisasikan, menginterpretasi, dan memberikan respon serta mengingat pesan yang disampaikan. Jadi dalam proses listening meliputi receiving, understanding, remembering, evaluating dan responding.
4. Kurangnya simpati apalagi empati pada keluarga yang memiliki anak autis.
Banyak yang tidak mengetahui bagaimana beratnya perjuangan yang mesti dilalui keluarga yang memiliki anggota keluarga yang autis. Baik sebagai orang tua, maupun sebagai saudara, mulai dari tahapan kesiapan psikologis, kesiapan finansial sampai pada kesiapan mental dalam menghadapi masyarakat, termasuk kesiapan ketika menghadapi stigmatisasi, diskriminasi, maupun perundungan dari masyarakat. Stigmatisasi merupakan proses mengkaji karakteristik dan identitas negatif kepada seseorang atau kelompok yang menyebabkan perasaan terkucil, tidak berguna dan terisolasi dari masyarakat luas. Jones (1984) menyatakan stigmatisasi terjadi karena anggapan atau prasangka, diskriminasi dan stereotyping. Stigma dapat dibedakan menjadi dua golongan, yakni stigma dari masyarakat (public stigma) dan stigma pada diri sendiri (self stigma) (Corrigan & Watson, 2002). Public stigma merupakan penilaian masyarakat terhadap kelompok tertentu, di mana penilaian berdasarkan sosial budaya yang dianut.
Dalam konteks keluarga anak autis, stigma yang mereka alami termasuk dalam kategori public stigma. Perilaku yang ditampilkan oleh masyarakat adalah dengan menghindari interaksi dengan keluarga yang memiliki anak autis dan tidak memberi kesempatan keluarga untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Autis dipandang sebagai aib atau hal-hal lainnya yang berimbas terhadap identitas sosial anak dan keluarga dalam lingkungannya. Stigma terhadap autis ini tentu makin memberatkan keluarga dan orang tua anak autis, dan menambah kekhawatiran keluarga terhadap masa depan anak dan harapan akan kesembuhan anak. Public stigma tentang isu autisme menjadi alasan tersendiri yang dapat menimbulkan keinginan keluarga untuk menutupi keberadaan anak dan mengisolasi diri dari kegiatan masyarakat. Hal ini senada dengan ungkapan Goffman (1986), bahwa penilaian negatif atau stigma dari masyarakat masih sering dialami oleh keluarga yang memiliki anak dengan kecacatan. Keluarga merasa malu memiliki anak yang berbeda dengan anak yang seusianya saat berkumpul dengan keluarga besar atau teman kerja bahkan keluarga harus menghadapi situasi dimana keluarga tidak diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat yang melibatkan seluruh anggota keluarga karena memiliki anak autis.
Masyarakat kita dengan pengetahuan yang mereka miliki, memandang autis sama dengan suatu penyakit yang bersifat menular atau identik bahkan disamakan dengan gila, keterbelakangan mental, kutukan dari dewa, kutukan dari penunggu suatu tempat atau benda, penyakit mistis, guna-guna atau kemasukan roh jahat. Tidak jarang anak-anak penyandang autis dijauhi oleh masyarakat sekitar karena dianggap bisa menularkan pada anak atau cucu mereka. Sementara si anak dijauhi dan dibully, orang tuanya dilanda rasa malu dan khawatir karena tidak ada penerimaan dari masyarakat setempat. Di beberapa daerah di Jawa, bahkan mungkin Indonesia, penyandang autis sering dianggap sebagai edan atau sinting. Sebagian masyarakat menerapkan pasung. Kaki penyandangnya diikatkan pada saka rumah. Bahkan di daerah seperti Wonogiri dan Ponorogo, dilakukan pemasungan kaki pada kayu yang telah dibentuk sedemikian rupa. Pasung dipandang masyarakat mampu untuk memberikan ketenangan bagi penyandangnya dan mengurangi rasa malu bagi orang tuanya karena sering dijadikan bahan pergunjingan oleh lingkungan sekitar ketika anak mereka berulah. Keluarga yang memiliki anggota penyandang autis dinilai masyarakat sebagai keluarga yang harus menanggung hukuman, dosa, atau kutukan. Keluarga merasakan adanya anggapan negatif, labeling, dan diskriminasi yang memengaruhi kehidupan mereka sehingga menumbuhkan keinginan menarik diri, secara fisik, sosial, dan membatasi diri untuk berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Keluarga yang memiliki anak autis membatasi diri dalam hal berinteraksi dengan lingkungan karena banyak keluarga besar, teman, dan masyarakat yang kurang memahami karakteristik perilaku anak penyandang autis.
Dengan memahami beberapa hal yang disebutkan di atas, diharapkan masyarakat lebih bisa memahami para penyandang autis dan keluarganya, menerima mereka sebagai bagian dari keberagaman di masyarakat. Mereka tidak menginginkan perlakuan istimewa, hanya penerimaan dari masyarakat. Jika tidak bisa membantu mengurangi beban mereka, minimal kita bisa meringankan beban mereka dengan menerima secara ikhlas keberadaan mereka di tengah masyarakat.

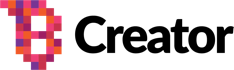





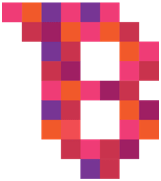




![[KUIS] tebak nama artis Tanah Air, dari potongan fotonya usai jalani operasi hidung](https://cdn-brilio-net.akamaized.net/webp/news/2024/07/26/293694/300x200-kuis-tebak-nama-artis-tanah-air-dari-potongan-fotonya-usai-jalani-operasi-hidung--240726v.jpg)






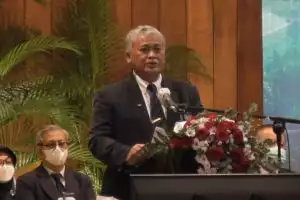




![[KUIS] Tipe helm yang kamu pakai ungkap seberapa besar tingkat kepedulian dengan diri sendiri](https://cdn-brilio-net.akamaized.net/webp/news/2024/07/26/293618/30x30-kuis-tipe-helm-yang-kamu-pakai-ungkap-seberapa-besar-tingkat-kepedulian-dengan-diri-sendiri-2407261.jpg)



![[KUIS] Benar atau salah saat hidung bayi mampet disedot dengan mulut? Cari tahu lewat kuis ini](https://cdn-brilio-net.akamaized.net/webp/news/2024/07/26/293612/30x30-kuis-benar-atau-salah-saat-hidung-bayi-mampet-disedot-dengan-mulut-cari-tahu-lewat-kuis-ini-240726y.jpg)





















