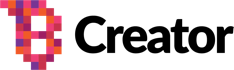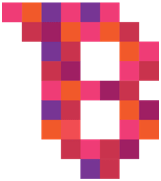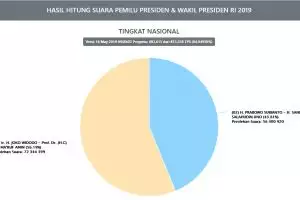Brilio.net - Anies Baswedan dan Sandiaga Uno baru saja dilantik Senin (16/10). Usai dilantik, Anies berpidato. Sayangnya, pidato Anies menuai kontroversi. Anies yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo ini memberi pidato bertema membebaskan diri dari kolonialisme.
Anies berbicara tentang kolonialisme yang semakin nyata. Dia menyinggung tentang keadaan pribumi dalam pidatonya tersebut. "Di Jakarta, kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Anies dilansir dari Merdeka.
Pidato ini banyak mendapat kritikan, salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. "Jadi jangan ada pribumi, non pribumi. Jangan dikotomiskanlah. Harus menjadi gubernur semua pihak, semua golongan, suku, agama, karena yang memilih Pak Anies juga kan macam-macam," ujar Luhut.
Anies sendiri sudah mengklarifikasi perihal pidato tersebut. Menurutnya istilah tersebut digunakan dalam konteks penjajahan. "Karena saya menulisnya pada era penjajahan dulu karena Jakarta kota yang paling merasakan, kalau kota-kota lain itu nggak merasakan Belanda secara dekat," kata Anies di ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/10) dikutip dari Merdeka.
Bagaimana sebenarnya awal mula penggunaan kata pribumi? Dulu pemerintah kolonial Belanda menyebut kelompok penduduk Hindia Belanda kepuluan Nusantara sebagai Inlanders atau jika diterjemahkan ke bahasa melayu menjadi pribumi.
Di sinilah permasalahan dimulai. Dilansir dari Encyclopedia of Modern Asia, Belanda yang pada saat itu diwakili oleh VOC membagi masyarakat Jakarta (dulunya bernama Batavia) menjadi tiga kelas. Kelas Eropa, Kelas Timur (Tionghoa, Arab, dan India), serta yang terakhir adalah kelas lokal nusantara. Buku terbitan Macmillan Reference USA itu juga menyebut politik adu domba atau devide et impera membuat interaksi antar kelas ini semakin susah.
Tidak semua nyaman dengan pembagian kelas sosial ini. Robert S. Elegant dalam bukunya The Dragon Seed tahun 1959 melihat bahwa warga keturunan Tionghoa terpaksa untuk menyendiri dari golongan lainnya. Mahbub Djunaidi Dalam bukunya Humor Jurnalistik (1986) melihat hal ini sebagai dinding penghalang untuk membaur secara kultural. Golongan kelas Timur terutama Tionghoa kesulitan untuk membaur dengan golongan lain. "Di masa kolonial, kami bagaikan binatang. Kami Kudu tinggal di daerah tertentu, tak bisa pilih sendiri," kutip Mahbud dari buku Robert.
Mahbub Djunaidi melihat perbedaan istilah pribumi dan non pribumi ini berbau motif ekonomi. Kesuksesan golongan Timur terutama Tionghoa menjadi pemicu dendam dari golongan pribumi. Dia sendiri mengusulkan tidak menggunakan istilah pribumi dan non pribumi, melainkan lebih tepat menggunakan 'yang kuat' dan "yang lemah".
Hal ini terlihat dari golongan kelas timur terutama Tionghoa yang mendominasi perekonomian Indonesia. Peristiwa 5 Agustus 1973 menjadi puncak dari gerakan rasialis yang membedakan pribumi dan non pribumi. Dalam peristiwa yang terjadi di Bandung tersebut, banyak warga keturunan Tionghoa yang menderita kerugian baik harta maupun nyawa. Kasus-kasus bernuansa rasial juga pernah terjadi, yakni tahun 1998.
Istilah pribumi tersebut sendiri sudah dilarang melalui Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998. Instruksi yang berlaku sejak 16 september 1998 tersebut mengatur tentang penghentian penggunaaan istilah pribumi dan non pribumi. Instruksi ini berlaku sejak ditandatangani oleh BJ Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai presiden.
Proses asimilasi ketiga golongan ini sudah berjalan walaupun pelan. Soekarno dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1964 menyebut persoalan bukan tentang berbedanya golongan masyarakat tapi bagaimana cara menyatukannya.
Perbedaan kondisi ekonomi dan status menjadi PR pemerintah agar bisa mendistribusikan kemakmuran dengan lebih merata. Yang menjadi pertanyaan sekarang bukan asal keturunan masyarakat dan membedakannya menjadi pribumi dan non pribumi.
Recommended By Editor
- Pendidikan tinggi bukan alasan mendapatkan gaji besar, kenapa ya?
- Produk halal berebut pasar kelas menengah muslim Indonesia
- Menggaet pasar milenial dari bisnis menonton
- Kenapa makanan sehat malah langka di era teknologi pengolahan pangan?
- Menelisik fenomena kematian akibat terlalu banyak kerja di Jepang