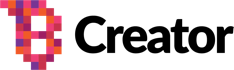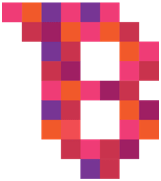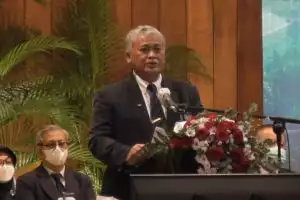Saat kamu atau keluargamu sakit dan kemudian dibawa ke rumah sakit akan menjumpai banyak orang yang mengenakan pakaian serba putih dan selalu patuh di samping dokter dengan jas putih (Berghs, Casterl, & Gastmans, 2006). Mereka bisa disebut sebagai perawat, dan kamu bisa selalu pastikan bahwa semuanya wanita anggun nan cantik. Bahkan, kita memanggilnya dengan panggilan yang sudah akrab di telinga, "suster". Namun, ada kalanya kamu juga akan menjumpai satu-dua sosok pria gagah dengan pakaian yang sama serba putih ketika harus berhadapan dengan pasien yang bertubuh besar atau mengalami gangguan kejiwaan. Lalu, siapa mereka?
Mereka juga perawat yang siap untuk mendedikasikan hidupnya demi merawat dan mempertahankan kesejahteraan klien yang berada dalam perawatannya. Hal ini mungkin membingungkanmu. Bukankah perawat yang sempurna harus bisa bersikap keibuan, penuh kasih dan lembut, serta tunduk dan patuh pada perintah dokter? Bagaimana mungkin, seorang laki-laki melakukan itu semua kalau tidak ada "keanehan" atau "maksud tersembunyi"ketika menyentuh pasien (Harding, North, & Perkins, 2008)?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah hal yang lumrah untuk ditanyakan. Selama ini, kita mengetahui bahwa seorang pria terlarang untuk bersikap lemah-lembut, menunjukkan perhatian, dan ketelatenan dalam merawat orang lain (Kuhse, Schklenk, & Singer, 2016)sifat feminin yang sempurna. Pria sejati diharapkan untuk selalu bertindak sesuai "maskulinitas prima", seperti bertindak secara tegas, dominan, penuh agresi, dan berpendirian teguh.
Kenyataannya, masih saja terdapat banyak pria yang mengabdikan diri mereka kepada profesi keperawatan. Negara-negara di dunia Timur, khususnya Asia, memiliki jumlah total perawat pria sebanyak kurang lebih 20% dari seluruh jumlah perawat; dibandingkan dunia Barat yang memiliki persentase 15% (Boniol, dkk., 2019). Kenyataan ini berbeda dengan disparitas dan ekspresi gender di kedua dunia tersebut, di mana dunia Barat lebih lentur dalam ekspresi gender seseorang. Oleh karena itu, meski jumlah perawat pria lebih sedikit, mereka lebih diterima dan tidak sering dikaitkan dengan feminitas dan kelemahan.
"Alasan utama banyaknya perawat pria di dunia Timur adalah kesempatan praktis untuk mendapatkan pendapatan secara cepat yang didukung dengan kondisi ekonomi negara-negara Timur. Padahal, perawat pria sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan karena kebutuhan pelayanan primer yang meningkat, tenaga fisik pria, dan preferensi gender dalam beberapa tindakan (Monroe & Kroning, 2020).
Situasi ini bisa kita lihat kembali dari karakteristik sempurna seorang perawat. Hasil riset Fisher (2011) menyatakan bahwa perawat ideal harus memiliki tabiat berikut: kasih sayang, hangat, sensitif, lembut, memahami, dan sabar. Tabiat atau ciri tersebut sangat dekat dengan ekspresi paripurna gender feminin (Zamanzadeh, dkk., 2013). Sosiologi dan antropologi sebagai disiplin akademik yang berfokus pada interaksi sosial manusia, telah mengamati dan menarik kesimpulan fenomena gender dalam masyarakat (University of Minnesota, 2020).
Masyarakat Timur utamanya mengharapkan semua anggota masyarakatnya untuk bersikap maskulin atau feminin yang sesuai dengan jenis kelamin mereka (Boehnke, 2011), walau telah ditemukan banyak variasi mengenai ekspresi gender; contohnya ada di masyarakat Bugis di Sulawesi yang mengenal lima gender (Graham, 2004). Oleh karena itu, keperawatanekspresi ideal feminitasdianggap sebagai satu-satunya profesi yang diperbolehkan bagi wanita untuk bekerja di luar rumah karena asosiasi wanita yang hanya boleh mengurus urusan internal rumah tangga (Berghs, Casterl, & Gastmans, 2006).

Lalu, bagaimana dengan masyarakat Barat dengan penerimaan terhadap perawat pria yang cukup umum? Pada abad pertengahan di Eropa, pengaruh gereja sangat kuat dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Biarawan-biarawan bertindak sebagai pemimpin rohani dan aktivis sosial. Mereka memberikan pelayanan perawatan bagi orang-orang yang sakit dan membuka banyak rumah-rumah perawatan tersebut (OLynn & Tranbarger, 2007). Boleh dikatakan, semua orang yang memberikan pelayanan keperawatan adalah pria-pria pengabdi gereja, dan dibantu oleh partner wanitanya yang mana menimbulkan persepsi publik untuk memanggil perawat sebagai "suster".Pemberi layanan perawatan dipandang sebagai sesuatu yang gender neutral, artinya baik pria maupun wanita boleh melakukannya.
Patriarki dan penyempitan ekspresi gender pada masa Viktoria menjadikan perawat pria hanya bisa menjalankan pekerjaannya sebagai perawat pada bidang-bidang militer, bencana, dan institusi kejiwaan (Christensen, 2017). Pria dianggap hanya bisa berpraktik di bidang tersebut karena mengandalkan ketangkasan dan kekuatan mereka, tidak seperti di lahan keperawatan umum, pediatri, atau bahkan maternitas. Ketimpangan ini diperkuat ketika tokoh keperawatan tersohor Florence Nightingale menyatakan dengan tegas bahwa keperawatan adalah profesi sejati wanita dan hanya bagi wanita (Smith C. M., 2018). Sejak saat itu, sekolah-sekolah keperawatan menutup admisi kepada pria meskipun juga masih terdapat yang membolehkan pria namun untuk jumlah terbatas dan fungsi terbatas (Black, 2017; OLynn & Tranbarger, 2007).
Lambat laun, negara-negara Barat membuka akses bagi pria untuk masuk ke dunia keperawatan, dengan legalisasi perawat pria untuk bergabung di Korps Militer Amerika-Kanada secara resmi pada tahun 1965 (OLynn & Tranbarger, 2007); hal tersebut adalah contoh pengakuan bagi pria untuk memasuki profesi keperawatan. Tetapi tetap saja, pria merepresentasikan jumlah kecil dalam keperawatan selama abad ke-20 di dunia. Perawat pria juga dianggap memiliki sifat-sifat homoseksual (Wolfenden, 2011).
"Meskipun pria boleh menjadi perawat, bukan berarti kebanyakan dari mereka termotivasi untuk menjadi perawat karena berbagai macam faktor: pengaruh keluarga, motivasi praktis (pemasukan dan keamanan pekerjaan perawat), dan personal (keberanian diri) (Zamanzadeh, dkk., 2013).
Semuanya berubah di pengujung abad ke-20 dan awal abad ke-21. Pria-pria di dunia Barat banyak yang memasuki dunia keperawatan karena terjadinya revolusi seksual dan gender di tahun 1960 hingga 1980-an (England, 2010). Konstruksi gender di dunia Barat melentur sehingga semua orang terlepas dari jenis kelamin mereka bisa menjadi profesi apa saja yang mereka inginkan. Kondisi ini didorong dengan perkembangan keperawatan yang semakin maju dan peluang praktik perawat yang luas (The College for The People, 2018). Sehingga, pria tidak takut lagi dan bangga untuk menjadi perawat di mata masyarakat, dan penyebutan netral "nurse"semakin memperkuat kondisi tersebut.
Kejadian yang terjadi di negara Timur memiliki sedikit perbedaan. Catatan sejarah tidak secara jelas membedakan fungsi antara perawat dengan praktisi kesehatan lain, karena mereka dianggap sama-sama penyembuh (Smith & Tang, 2004). Penyembuh ini mempraktikkan pengobatan tradisional dan alternatif sepanjang sejarah dunia Timur sebagai pengobatan utama yang diterima oleh masyarakat; dan keluarga mereka yang memberikan perawatan kepada orang yang sakit (Smith & Tang, 2004). Oleh karena itu, kesehatan dipandang sebagai keseimbangan holistik seluruh aspek kehidupan, terlepas dari konstruksi gender yang ada.
Kolonialisme dan imperialisme negara Barat kepada berbagai negara lain di dunia, khususnya negara Timur, membawa budaya mereka bersamanya. Tanah koloni mereka yang selama ini mengenal pengobatan yang bersifat holistik, akhirnya terpapar pada pengobatan ala Barat (Smith & Tang, 2004). Bukan hanya model pengobatan saja, model tenaga kesehatan juga dibawa dan dipaparkan kepada koloni mereka.
Utamanya, mereka membawa model patriarki di mana dokter pria adalah otoritas penuh dalam pelayanan kesehatan, dan mereka membutuhkan asisten dokter dari kelas pribumi elite (Radiopoetro, 1976).
Asisten dokter, yang juga pria, selalu patuh pada setiap perintah dokter dan bertindak secara langsung dalam merawat pasien, meski belum ada okupasi formal keperawatan. Hierarki sosial dan kesehatan saat itu adalah: pria Barat atau dokter sebagai kelas satu, pria pribumi atau asisten dokter sebagai kelas dua, dan wanita pribumi sebagai kelas tiga (Mancini, 2012).
Ketika koloni-koloni ini merdeka, utamanya Indonesia, asisten dokter tersebut naik derajat sebagai dokter seutuhnya.
Mereka kemudian membutuhkan kaki tangan untuk membantunya, yang kemudian mereka akhirnya merekrut wanita-wanita (kelas di bawahnya) untuk menjadi perawat (Shields & Hartati, 2003). Meskipun wanita tetap mendominasi, dapat ditemukan pula pria yang menempuh pendidikan keperawatan terlepas dari stigma dan persepsi gender dalam masyarakat (Shields & Hartati, 2003).
Kebanyakan dari mereka ingin segera bekerja dalam waktu yang cepat dan biaya yang murah; keperawatan adalah bidang yang cocok akan hal itu. Setelah lulus, mereka bisa bekerja di rumah sakit sebagai kembali lagi, asisten dokter, atau di masyarakat sebagai medik dan dikenal dengan panggilan mantri (Hesselink, 2015).
Pria-pria lain lulusan pendidikan keperawatan Indonesia yang menekuni disiplin ilmu keperawatan ikut membantu perkembangan profesi keperawatan. Mereka menginisiasi profesionalisme keperawatan dengan membentuk organisasi profesi, pendirian pendidikan sarjana keperawatan, dan sekolah ke luar negeri di mana keperawatan telah berkembang sebagai profesi yang sejajar dengan profesi lain. Usaha mereka tetap berlanjut meskipun prevalensi stigma bahwa harusnya seorang wanita masih banyak. Kesuksesan profesionalisasi keperawatan menarik lebih banyak pria untuk menjadi perawat, meskipun dasar alasannya tetap sama seperti dahulu.
Sama seperti di negara Barat, perawat pria lebih banyak ditemukan di masyarakat, militer, dan institusi kejiwaan (OLynn & Tranbarger, 2007). Hal ini cukup wajar, mengingat Indonesia masih belum memiliki adanya suatu revolusi sosial tentang gender karena kentalnya norma sosial dan agama (Robinson, 2016). Bahkan, negara-negara Barat membolehkan pria untuk berpraktik di lahan kebidanan atau kesehatan wanita (Pilkenton & Schorn, 2008). Kondisi ini tentunya berbeda dengan Indonesia yang menyatakan secara eksklusif bahwa bidan harus seorang wanita (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan) dan perawat pria di lahan kesehatan wanita sangat sedikit akibat diskriminasi gender (Latifah & Anggraeni, 2014). Kondisi ini tetap berlangsung di Indonesia hingga masa modern sekarang.

Perbandingan persepsi dan konstruksi gender di kedua belahan dunia ini sangat menarik untuk diamati. Dunia Barat adalah pelopor bagi profesionalisasi perawat dan penyuaraan netralitas gender di keperawatan. Meskipun begitu, pria tidak selalu menjadi subjek kelas dua di keperawatan Barat. Contohnya, perawat pria menerima pendapatan yang lebih dari perawat wanita dengan beban kerja yang sama, bahkan bisa beribu-ribu dolar Amerika Serikat (Maier, 2015). Oleh karena itu, ketimpangan gender tidak hanya terjadi pada satu sisi saja, namun pada semua gender terjadi ketidakstabilan dan ketidaksetaraan dalam dunia keperawatan.
Konstruksi sosial gender seharusnya bukan menjadi hambatan atau larangan bagi pria yang ingin menyelami dunia keperawatan. Maskulinitas sejati ditentukan oleh keberanian diri seorang pria untuk menjadi dirinya sendiri (Koerner, 2018). Keberanian tersebut akan menuntun mereka untuk tetap tabah, sabar, dan tegar dalam menghadapi semua stigma buruk yang ada dalam masyarakat. Profesi keperawatan sendiri adalah profesi yang sangat menjanjikan, dengan bisa memberikan perbedaan bagi orang lain, lapangan pekerjaan yang luas, permintaan tenaga perawat yang selalu meningkat, dan pendapatan yang memuaskan (Brooks, 2019). Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan atau halangan bagi pria untuk menjadi perawat yang mulia.
Indonesia sendiri sebagai sebuah negara industri baru dan sedang berkembang di panggung internasional, harus berkaca pada situasi negara lain. Seluruh masyarakat Indonesia harus menghapus pandangan dan mentalitas bahwa perawat pria adalah seorang yang lemah, ringkih, kewanitaan, atau terpaksa menjadi perawat. Sosialisasi oleh organisasi dan institusi pendidikan keperawatan harus gencar dilaksanakan untuk mengampanyekan inklusivitas keperawatan dan menghapus ketimpangan gender yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia bisa secara aktif mempromosikan peluang kerja bagi pria-pria untuk masuk di dunia keperawatan; mereka juga bisa mencanangkan legislasi terhadap perlindungan segala bentuk diskriminasi di tempat kerja maupun sosial masyarakat. Dengan begitu, Indonesia dapat mencapai pelayanan kesehatan yang seimbang dan optimal bagi kesejahteraannya.
Akhir kata, keperawatan adalah dunia yang dinamis dan cermin nyata fenomena sosial suatu masyarakat. Sepanjang sejarahnya, keperawatan berperan penting untuk penyetaraan gender dan penghapusan stigma buruk masyarakat.
Perawat adalah agen perubahan, yang mana tugasnya juga sebagai pengubah konstruksi kolot masyarakat dan penghapus diskriminasi.Keseimbangan sosial yang baik tercipta ketika semua orang dipandang berdasarkan apa kontribusinya bagi dunia, dan bukan dari penampilan fisiknya.
*Artikel ini ditulis untuk memperingati Hari Perawat Internasional (12 Mei) dan Tahun Perawat dan Bidan (2020) yang dirayakan setiap tanggal dalam rangka 200 tahun hari lahir Florence Nightingale, tokoh pelopor keperawatan modern.
Source
- Berghs, M., Casterle, B. D., & Gastmans, C. (2006, Februari). Nursing, obedience, and complicity with eugenics: a contextual interpretation of nursing morality at the turn of the twentieth century. Journal of Medical Ethics, 32(2), 117-122. doi:10.1136/jme.2004.011171
- Black, B. P. (2017). Professional Nursing (Concepts and Challenges) (8 ed.). St. Louis, Missouri: Elsevier, Inc.
- Boehnke, M. (2011). Gender Role Attitudes around the Globe: Egalitarian vs. Traditional Views. Asian Journal of Social Science, 39(1), 57-74. Dipetik Mei 8, 2020, dari www.jstor.org/stable/43500538
- Boniol, M., McIsaac, M., Xu, L., Wuliji, T., Diallo, K., & Campbell, J. (2019). Gender equity in the health workforce: Analysis of 104 Countries. Geneva: World Health Organization. Dipetik dari https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311314/WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-eng.pdf
- rooks, A. (2019, November 3). Is Nursing a Good Career? Nurses Dish the Details. Dipetik dari Rasmussen College: https://www.rasmussen.edu/degrees/nursing/blog/is-nursing-good-career/
- Christensen, M. (2017, Januari 3). Men in nursing: The early years. Journal of Nursing Education and Practice, 7(5), 94-103. doi:10.5430/jnep.v7n5p94
- Fisher, M. J. (2011). Sex differences in gender characteristics of Australian nurses and male engineers: A comparative cross-sectional survey. Contemporary Nurse, 39(1), 36-50. Dipetik dari https://www.researchgate.net/profile/Murray_Fisher/publication/51677987_Sex_differences_in_gender_characteristics_of_Australian_nurses_and_male_engineers_A_comparative_cross-sectional_survey/links/53fec7aa0cf283c3583be75f/Sex-differences-in-gender-charact
- Graham, S. (2004). It's Like One of Those Puzzles: Conceptualising Gender Among Bugis. Journal of Gender Studies, 13(2), 107-116. doi:10.1080/0958923042000217800
- Harding, T., North, N., & Perkins, R. (2008). Sexualizing Men's Touch: Male Nurses and the Use of Intimate Touch in Clinical Practice. Research and Theory for Nursing Practice: An International Journal, 22(2), 88-102. doi:10.1891/0889-7182.22.2.88
- Hesselink, L. (2015). The early years of nursing in the Dutch East Indies, 189-1920. Dalam H. Sweet, & S. Hawkins (Penyunt.), Colonial Caring (A History of Colonial and Post-Colonial Nursing) (hal. 145-168). Manchester, England: Manchester University Press. Dipetik dari https://pdfs.semanticscholar.org/4ff4/14979703cad510200ad07bb9fdc4a4a2554d.pdf
- Koerner, R. (2018, April 1). The Cure for ?Toxic? Masculinity Is Real Masculinity. Dipetik dari Huffpost: https://www.huffpost.com/entry/the-cure-for-toxic-masculinity-is-real-masculinity_b_5a4dc4bfe4b0df0de8b06f81
- Kuhse, H., Sch?klenk, U., & Singer, P. (Penyunt.). (2016). Bioethics (An Anthology) (3 ed.). West Sussex: John Wiley & Sons, Inc.
- Latifah, L., & Anggraeni, M. D. (2014, Juli). Pengalaman Praktik Mahasiswa Pria dalam Praktik Profesi Keperawatan Maternitas yang Bias Gender. Jurnal Keperawatan Soedirman, 9(3), 146-155.
- Maier, S. (2015, Maret 26). Male Registered Nurses Make Thousands More in Salary Than Female Counterparts. Dipetik dari University of California San Francisco: https://www.ucsf.edu/news/2015/03/124266/male-registered-nurses-make-thousands-more-salary-female-counterparts
- Mancini, S. (2012, Maret 30). Patriarchy as the exclusive domain of the other: The veil controversy, false projection and cultural racism. International Journal of Constitutional Law, 10(2), 411-428. doi:doi.org/10.1093/icon/mor061
- Monroe, I., & Kroning, M. (2020). It is Time to Recruit More Men into the Profession of Nursing. Dipetik dari RN Journal: https://rn-journal.com/journal-of-nursing/time-to-recruit-more-men-into-the-profession-of-nursing
- O?Lynn, C. E., & Tranbarger, R. E. (Penyunt.). (2007). Men in Nursing (History, Challenges, and Opportunity). New York: Springer Publishing Company, LLC.
- Pilkenton, D., & Schorn, M. N. (2008, Februari). Midwifery: A career for men in nursing. Men in Nursing, 29-33. Dipetik dari https://nursing.vanderbilt.edu/msn/pdf/nmw_midwiferyformen.pdf
- Radiopoetro. (1976). Sejarah Pendidikan Dokter di Indonesia. Berkala Ilmu Kedokteran, 8(4), 141-150. Dipetik dari https://journal.ugm.ac.id/bik/article/view/4753/4005
- Shields, L., & Hartati, L. E. (2003, Juni). Nursing and health care in Indonesia. Journal of Advanced Nursing, 44(2), 209-216. doi:10.1046/j.1365-2648.2003.02785.x
- Smith, C. M. (2018). A Male Perspective on Being a Nurse in Today's Healthcare Environment. Appalachian State University, Nursing. Boone: Appalachian State University Graduate School. Dipetik dari http://libres.uncg.edu/ir/asu/f/Smith_Chris_2018_Thesis.pdf
- Smith, D. R., & Tang, S. (2004). Nursing in China: Historical development, current issues and future challenges. ????????, 5(2), 16-20. Dipetik dari https://www.researchgate.net/publication/228737679_Nursing_in_China_Historical_development_current_issues_and_future_challenges
- The College for The People. (2018, Oktober 16). How Stable Is a Nursing Career: Nursing Jobs Demand. Dipetik dari Nightingale College: https://nightingale.edu/blog/nursing-jobs-demand/
- University of Minnesota. (2020). 11.1 Understanding Sex and Gender. Dipetik dari University of Minnesota Open Library: https://open.lib.umn.edu/sociology/chapter/11-1-understanding-sex-and-gender/
- Wolfenden, J. (2011, April). Men in Nursing. The Internet Journal of Allied Health Science and Practice, 9(2), 1-6. Dipetik dari https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1347&context=ijahsp
- Zamanzadeh, V., Valizadeh, L., Negarandeh, R., Monadi, M., & Azadi, A. (2013, Desember 2). Factors Influencing Men Entering the Nursing Profession, and Understanding the Challenges Faced by Them: Iranian and Developed Countries? Perspectives. Nursing and Midwifery Studies, 49-56. doi:10.5812/nms.12583